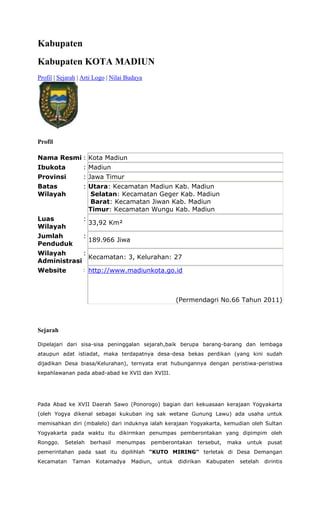Madiun
- 1. Kabupaten Kabupaten KOTA MADIUN Profil | Sejarah | Arti Logo | Nilai Budaya Profil Nama Resmi : Kota Madiun Ibukota : Madiun Provinsi : Jawa Timur Batas : Utara: Kecamatan Madiun Kab. Madiun Wilayah Selatan: Kecamatan Geger Kab. Madiun Barat: Kecamatan Jiwan Kab. Madiun Timur: Kecamatan Wungu Kab. Madiun Luas : 33,92 KmÂē Wilayah Jumlah : 189.966 Jiwa Penduduk Wilayah : Kecamatan: 3, Kelurahan: 27 Administrasi Website : http://www.madiunkota.go.id (Permendagri No.66 Tahun 2011) Sejarah Dipelajari dari sisa-sisa peninggalan sejarah,baik berupa barang-barang dan lembaga ataupun adat istiadat, maka terdapatnya desa-desa bekas perdikan (yang kini sudah dijadikan Desa biasa/Kelurahan), ternyata erat hubungannya dengan peristiwa-peristiwa kepahlawanan pada abad-abad ke XVII dan XVIII. Pada Abad ke XVII Daerah Sawo (Ponorogo) bagian dari kekuasaan kerajaan Yogyakarta (oleh Yogya dikenal sebagai kukuban ing sak wetane Gunung Lawu) ada usaha untuk memisahkan diri (mbalelo) dari induknya ialah kerajaan Yogyakarta, kemudian oleh Sultan Yogyakarta pada waktu itu dikirmkan penumpas pemberontakan yang dipimpim oleh Ronggo. Setelah berhasil menumpas pemberontakan tersebut, maka untuk pusat pemerintahan pada saat itu dipilihlah "KUTO MIRING" terletak di Desa Demangan Kecamatan Taman Kotamadya Madiun, untuk didirikan Kabupaten setelah dirintis
- 2. pembangunannya kemudian digeser ke utara lagi yaitu ditengah Kotamadya Madiun sekarang di Komplek Perumahan Dinas Bupati Madiun. Disinilah seterusnya Ronggo ke I s/d ke III menjalankan pemerintahan, sedangkan makamnya ada di Desa Taman (dulu Desa Perdikan). Jadi status DEsa Perdikan Taman maupun KUncen, sbegai wilayah Kerajaan Yogyakarta karena disitu disemayamkan pahlawan-pahlawan pada zaman lampau, sehingga kepada orang yang dipercaya menjaga/merawat makam tersebut diberikan hadiah sebagai sumber pencahariannya, satu wilayah Pedesaan serta hak untuk memungut hasilnya, bersifat Orfelijik (turun tumurun). Pada Abad ke XVII di zaman peperangan Diponegoro, munculah salah seorang putera Ronggo (Rongggo ke II) yang dikenal dengan nama "Ali Basah Sentot Prawirodirdjo". Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropha yang lain sehingga, Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal apa arti politik dan sosial ekonomi yang terdapat di Madiun, tetapi setelah perang Diponegoro berakhir Madiun menjadi pertahanan terakhir pasukan Diponegoro mulai dikenal oleh orang- orang Belanda arti politik dan sosial ekonomi, banyak daerah pertanian diubah menjadi perkebunan. Pada tanggal 1 Januari 1832 Madiun secara resmi dikuasai oleh Pemerintah Hindia belanda dan dibentuklah suatu Tata Pemerintahan yang berstatus "KARISIDENAN" Ibu Kota Karisidenan berlokasi di Desa Kartoharjo (tempat Patih Kartohardjo) yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Pangongangan. Sejak saat itu mulailah berdatangan bangsa Belanda atau Eropha yang lain berprofesi dalam bidang perkebunan tebu dengan Pabrik Gulanya seperti PG. Sentul (Kanigoro), PG. Pagotan (Uteran), PG. Rejoagung (Patihan) milik orang cina. Kecuali itu muncul pula perkebunan teh di Jamus dan Dungus, Kopi di Kandangan, Tembakau di Pilangkenceng, semua warga negara eropha bermukim di tengah kota sekitar istana Residen Madiun, supaya tidak kena pengaruh orang Madiun yang pemeberani karena bekas kotanya merupakan tempat pusat pertahanan wilayah timur Mataram (Monconegoro Timur) yang anti belanda. Maka segresi sosial (pemisahan sosial) harus dilakukan. Dikandung maksud untuk membendung jangkuan pengaruh kaum pergerakan rakyat indonesia, maka perlu mengubah ketatanegaraan di Madiun yakni Kota yang berdiri sendiri dimana pemimpimnya tetap bangsa belanda, masyarakat sebagian besar orang asing. Dan lagi pula kerajaan belanda telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur daerah perkotaan yang disebut : Inlandsche Gemeente Ordonantie yang dikeluarkan pada tahun 1906 oleh Departemen Binnenlandsch Bestuur yang dalam hal itu oleh Menteri S. De Graaf
- 3. Maka wilayah perkotaan Madiun dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi Stadsgemeente Madiun atau Kota Praja Madiun atau Haminte Madiun. Kotapraja madiun berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918 dengan landasan Staatsblad Tahun 1918 Nomor 326, sehingga wilayah itu dikepalai oleh seorang Burgemeester yang pertama dijabat oleh Ir.M.K. Ingenlijf semula menjabat asisten residen Madiun (modalnya terdiri dari 12 pedesaan yakni Madiun Lor, Sukosari, Patihan, Oro Oro Ombo, Kartoharjo, Pangongangan, Kejuron, Klegen, Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Pandean, Taman yang administratif berstatus Desa Perdikan dibawah naungan keraton Yogyakarta yang kemudian diganti oleh De Maand hingga tahun 1927. Sedangkan lembaga dan jabatan Walikota Madiun baru diadakan 10 tahun kemudian dengan dikeluarkan staatsblad nomor 14 tahun 1928. Arti Logo Berdasakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1970 Makna Lambang 1. Perisai sebagai dasar lambang dasar Warna Hijau Tua, bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas ialah pembinaan, keselamatan dan kesejahteraan pemduduk dan pemerintah ; 2. Dua Gunung dan Sungai warna biru dan putih, langit cerah warna kuning serta tanah subur warna hijau muda, bermakna letak kota Madiun di daerah yang subur, diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis dimana mengalir Bengawan Madiun ; 3. Fondamen terdiri atas 5 batu utama warna merah, bermakna dasar Pemerintah Daerah yang demokratis bersendi Pancasila ; 4. Tugu Warna putih, bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamsi 17 Agustu 1945 ; 5. Keris Pusaka Tundung Madiun warna hitam, bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya ;
- 4. 6. Padi dan Kapas warna kuning emas, setangkai padi terdiri dari atas 17 butir, setangkai kapas terdiri dari atas 8 bunga dan sembilan daun bermakna kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 Makna Warna Pada Gambar 1. Hijau-tua dan Hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan ; 2. Kuning dan Kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan ; 3. Biru berarti ketentraman dan kesetian ; 4. Putih berarti kesucian ; 5. Merah berarti keberanian ; 6. Hitam berarti keabadian. Arti/makna keseluruhan lambang Daerah Kota Madiun adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian, sebagai pelindung rakyat, mengabdi dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustu 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera Pancasila Nilai Budaya
- 5. Lambang Daerah dan Artinya Perisai Bersudut Lima, melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepulauan Bangka Belitung, melambangkan wilayah, masyarakat, sistem pemerintah, kebudayaan dan sumberdaya alam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lingkaran Bulat Simetrikal, melambangkan kesatuan dan persatuan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi segala tantangan di tengah-tengah peradaban dunia yang semakin terbuka. Butir Padi berjumlah 27 buah melambangkan nomor dari Undang-undang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu UU No.27 Tahun 2000,dan Buah Lada, berjumlah 31 buah melambangkan Kepulauan Bangka Belitung merupakan Propinsi ke 31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padi dan buah lada juga melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Balok Timah, melambangkan kekayaan alam (hasil bumi pokok) berupa timah yang dalam sejarah secara social ekonomis telah menopang kehidupan masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lebih dari 300 tahun. (diketemukan dan dikelola sejak tahun 1710 Mary Schommers dalam Bangka Tin). Biru Tua dan Biru Muda (Dalam Perisai dan Lingkaran Hitam), melambangkan bahari dunia kelautan dari yang dangkal sampai yang terdalam. Menyiratkan lautan dengan segala kekayaan alam yang ada di atasnya, di dalam dan di dasar lautan yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Putih (Tulisan), melambangkan keteguhan dan perdamaian. Kuning ( Padi dan Semboyan), melambangkan ketentraman dan kekuatan. Hijau (Pulau dan Lada), melambangkan kesuburan. Hitam (Outline Lingkaran), melambangkan ketegasan. Serumpun Sebalai, menunjukan bahwa kekayaan alam dan plularisme masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap merupakan kelurga besar komunitas (serumpun) yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan , kemakmuran, keadilan dan perdamaian. Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, dengan budaya masyarakat melayu berkumpul, bermusyawarah, mufakat, berkerjasama dan bersyukur bersama-sama dalam semangat kekeluargaan (sebalai) merupakan wahana yang paling kuat untuk dilestarikan dan
- 6. dikembangkan. Nilai- nilai universal budaya ini juga dimiliki oleh beragam etnis yang hidup di Bumi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, Serumpun Sebalai mencerminkan sebuah eksistensi masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kesadaran dan citacitanya untuk tetap menjadi keluarga besar yang dalam perjuangan dan proses kehidupannya senantiasa mengutamakan dialog secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta berkerja sama dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Serumpun Sebalai, merupakan semboyan penegakan demokrasi melalui musyawarah dan mufakat. Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- 7. Arti Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Lambang Prop. Sulsel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 yang menggambarkan unsur-unsur historis, kultural, patriotik, sosiologis, ekonomi dan menunjukkan bahwa Daerah Sulsel merupakan bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang daerah tersebut terdiri atas tujuh bagian yaitu dengan masing-masing makna sebagai berikut : 1. Bintang bersudut dan bersinar lima; sebagai Nur cahaya yang mewujudkan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Lingkaran 17 buah padi dan 8 kapas dengan kelopak bergerigi 4 dan buah bergerigi 5 melambangkan 17-8-45 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Benteng Somba Opu dilihat dari atas; mewujudkan lambang kepahlawanan rakyat Indonesia Sulsel dalam menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan feodalisme. Terdiri ruang benteng masing-masing berisi : 1. Perahu phinisi berlayar di atas tiga gelombang melambangkan jiwa pelaut yang ulet, penuh milintasi dan sanggup melaksanakan tujuan perjuangan 17 Agustus 1945. Perahu berhaluan ke barat, disesuaikan dengan letak geografis Ibukota Republik Indonesia. 2. Pacul menggambarkan masyarakat agraris sebagai basis dan gerigi mesin menggambarkan industri sebagai tulang punggung. 3. Buah kelapa menggambarkan kekayaan hasil bumi Sulawesi Selatan 4. Sebilah badik terhunus berpamor satu berklekuk 5; melambangkan jiwa kepahlawanan serta kesiapsiagaan dalam membela kehormatan bangsa dan tanah air yang berdasarkan Pancasila. Lima lekuk pamor disesuaikan bilangan-bilangan keramat tiap sila dalam falsafah Pancasila. 5. Gunung, desa, dan petak-petak sawah; sebagai pangkal kesuburan menuju masyarakat adil dan makmur. 23 petak sawah disesuaikan dengan jumlah daerah tingkat II di Sulawesi Selatan yang keseluruhannya merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia. 6. Sebuah semboyan ditulis dalam huruf Lontara yang berbunyi Toddoâpuli; sebagai semboyan masyarakat Sulsel yang bermakna teguh dalam keyakinan 7. Selembar pita bertuliskan âSulawesi Selatanâ, sebagai salah satu propinsi di Indonesia. Pita bercorak sutera melambangkan kebudayaan khas yang bernilai tinggi sejak dahulu kala.
- 8. Arti Bentuk Lukisan Lambang Lambang Daerah Kabupaten Padang Pariaman berbentuk perisai bersegi lima, diatas dasar hijau yang dihiasi dengan : Didalamnya/ditengah-tengah, berdiri sebuah Balairung Adat Bergonjong Lima yang beratap Ijuk (hitam) berdinding hitam. Disamping kiri dan kanan Balirung Adat, terdapat dua batang pohon kelapa berwarna hijau yang mempunyai pelapah lima belas buah Disebelah bawah Balairung Adat, terdapat dua jalur warna biru bergelombang, membayangkan adanya lautan diatas dasar putih. Warna merah melengkung diatas balairung adat, adalah busur/panah dan diujung anak panah ada sebuah bintang bersegi lima. Pada bahagian sebelas atas, tertulis judul Padang Pariaman dan bahagian sebelah bawah tertulis Motto SAIYO SAKATO diatas dasar kuning. Arti Motto SAIYO SAKATO Pada bahagian sebelas atas, tertulis judul Padang Pariaman dan bahagian sebelah bawah tertulis Motto SAIYO SAKATO diatas dasar kuning. Arti Gambar Balairung Melambangkan bahwa rakyat daerah Kabupaten Padang Pariaman Adat mematuhi/menghormati dan melaksanakan ketentuan Adat Minangkabau dan juga lambang tempat permusyawaratan yang menjunjung tinggi Demokrasi. Bintang Merupakan bahagian dari Lambang Negara yakni Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa. Pohon Kelapa Lambang kesatuan yang merupakan tanaman utama di daerah Padang Pariaman dengan jumlah pelapah daun 17 buah, menunjukkan banyaknya Kecamatan yang ada dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Panah Lambang patriotisme, senjata sakti untuk mempertahankan hak atas jalan kebenaran, musuh tidak dicari-cari (basuo pantang dielakkan). Lautan Melambangkan masyarakat yang dinamis, kreatif yang merupakan manifestasi dari alam fikiran dan perikehidupan masyarakat yang berpaham luas dan berfikiran tenang. Laut juga merupakan bahwa Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai daerah lautan yang luas.
- 9. Lambang Gorontalo Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi, cari Lambang Gorontalo Lambang Gorontalo memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Bagian luar berbentuk perisai atau jantung yang memberi makna kesetiaan sebagai pelindung kehidupan rakyat Gorontalo Bagian dalam berbentuk bulat lonjong atau bulat telur yang memberi makna adanya gagasan, ide atau cita-cita yang indah, yang kelak menetas menjadi sesuatu kesejahteraan hidup rakyat Gorontalo. Bentuk dalam menampakkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna putih di tengah dan diikuti oleh posisi padi - bintang, kapas - rantai memberi makna adanya keteraturan adat, agama, hukum dalam semua pola kehidupan masyarakat. Memiliki nuansa global o Warna biru keunguan adalah warna yang memberi makna tenang, setia dan selalu ingin mempertahankan kebenaran dan harapan masa depan yang cerah o model pohon kelapa yang melengkung memberi makna gerak dinamis dan tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa depan o Sayap maleo yang mengembang memberi makna dinamika siap untuk tinggal landas dan siap bersaing o Buku yang terbuka melambangkan keinginan masyarakat untuk untuk siap meraih prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa secara terus menerus o Bintang mengandung makna global jika dikaitkan dengan cita-cita yang tinggi yaitu "Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit" o Pita mempunyai makna keinginan masyrakat Gorontalo untuk menyerap, merekam dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi Memiliki nuansa nasional o Padi dan kapas yang mengandung makna kemakmuran dan kesejahteraan seperti pada Pancasila o Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika Memiliki nuansa lokal o Bintang adalah lambang keagamaan, sehingga selaras dengan filosofi "Adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah" o Benteng o Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika Pemaknaan warna dan simbol-simbol lainnya dalam lambang o Simbol rantai yang memberi makna pada peristiwa patriotik ï§ Rantai yang berjumlah 23 butir melambangkan tanggal 23 Januari
- 10. ï§ Kapas yang berjumlah 19 buah dan padi berjumlah 42 butir melambangkan tahun 1942 o Sayap maleo yang berjumlah 16 helai melambangkan lahirnya Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2000 o Warna: ï§ Hijau: kesuburan ï§ Kuning: keagungan dan kemuliaan ï§ Putih: kesucian dan keluhuran ï§ Merah: keberanian dan perjuangan
- 11. PENGUMUMAN 1. Perlu kami sampaikan Standar Operasional Prosedur Pendataan NUPTK tahun 2012 yang dikeluarkan Oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud, bahwa NUPTK sejak 1 Januari 2012 diberikan hanya kepada Guru Tetap Yayasan di Sekolah Swasta atau Guru PNS. Guru Tidak Tetap di sekolah swasta harus memiliki SK PENGANGKATAN dari KETUA YAYASAN (bukan Kepala Sekolah) dan bagi Guru Tidak Tetap di sekolah negeri harus memiliki SK PENGANGKATAN dari Bupati/Walikota. 2. Terkait hal tersebut, kami sampaikan bahwa perbaikan data NUPTK bagi GURU YG TELAH MEMILIKI NUPTK telah kami laksanakan bulan Juli-Agustus 2012 melalui Lembar Koreksi Data (LKD). Sedangkan PENGAJUAN NUPTK BARU belum dapat difasilitasi sampai waktu yang belum ditentukan oleh Tim NUPTK Pusat. Sehingga kami dari Tim NUPTK Provinsi Jawa Tengah juga masih menunggu perubahan kebijakan dari Pusat. 3. NUPTK yang sudah terbit dapat dilihat di nuptk.kemdikbud.go.id. 4. Verifikasi ulang NUPTK akan kami laksanakan akhir Oktober, Bagi GURU BER NUPTK untuk menjaring perbaikan data yang belum masuk dalam Updating Data Bulan Juli- Agustus.
- 12. Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2012 . Gaji pokok PNS ini diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Berikut Tabel Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2012 berdasarkan masa kerja per golongan : Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2012 Masa Kerja Golongan I a b c d 0 1.260.000 1 2 1.297.600 3 1.372.700 1.430.800 1.491.300 4 1.336.400 5 1,413,700 1,473,500 1,535,800 6 1.376.300 7 1,455,900 1,517,500 1,581,700 8 1.417.400 9 1,499,400 1,562,800 1,628,900 10 1.459.700 11 1,544,100 1,609,500 1,677,500 12 1.503.300 13 1,590,300 1,657,500 1,727,600 14 1.548.200 15 1,637,700 1,707,000 1,779,200 16 1.594.400 17 1,686,600 1,758,000 1,832,300 18 1.642.000 19 1,737,000 1,810,500 1,887,000 20 1.691.000 21 1,788,900 1,864,500 1,943,400 22 1.741.500 23 1,842,300 1,920,200 2,001,400 24 1.793.500 25 1,897,300 1,977,500 2,061,200 Ipad Fat Loss Video Diet Fat Lesson Burning Offer Foods From Burn Ipad Tom Pete You Venuto Made A Presents, Smart Burn The Decision Fat, Feed Investing The Your Muscle Hard- Fat earned Burning Money Secrets In... Of The... 26 1.847.000
- 13. 27 1,953,900 2,036,600 2,122,700 Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2012 Masa Golongan II Kerja a b c d 0 1,624,700 1 1,648,900 2 3 1,698,200 1,770,000 1,844,900 1,922,900 4 5 1,748,900 1,822,900 1,900,000 1,980,300 6 7 1,801,100 1,877,300 1,956,700 2,039,500 8 9 1,854,900 1,933,300 2,015,100 2,100,400 10 11 1,910,300 1,991,100 2,075,300 2,163,100 12 13 1,967,300 2,050,500 2,137,200 2,227,700 14 15 2,026,000 2,111,700 2,201,100 2,294,200 16 17 2,086,500 2,174,800 2,266,800 2,362,700 18 19 2,148,800 2,239,700 2,334,500 2,433,200 20 21 2,213,000 2,306,600 2,404,200 2,505,900 22 23 2,279,100 2,375,500 2,475,900 2,580,700 24 25 2,347,100 2,446,400 2,549,900 2,657,700 26 27 2,417,200 2,519,400 2,626,000 2,737,100 28 29 2,489,400 2,594,700 2,704,400 2,818,800 30 31 2,563,700 2,672,100 2,785,200 2,903,000 32 33 2,640,200 2,751,900 2,868,300 2,989,600
- 14. Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2012 Masa Golongan III Kerja a b c d 0 2,064,100 2,151,400 2,242,400 2,337,300 1 2 2,125,700 2,215,700 2,309,400 2,407,100 3 4 2,189,200 2,281,800 2,378,300 2,478,900 5 6 2,254,600 2,349,900 2,449,300 2,552,900 7 8 2,321,900 2,420,100 2,522,500 2,629,200 9 10 2,391,200 2,492,400 2,597,800 2,707,700 11 12 2,462,600 2,566,800 2,675,300 2,788,500 13 14 2,536,100 2,643,400 2,755,200 2,871,800 15 16 2,611,900 2,722,300 2,837,500 2,957,500 17 18 2,689,800 2,803,600 2,922,200 3,045,800 19 20 2,770,100 2,887,300 3,009,500 3,136,800 21 22 2,852,900 2,973,500 3,099,300 3,230,400 23 24 2,938,000 3,062,300 3,191,900 3,326,900 25 26 3,025,800 3,153,700 3,287,200 3,426,200 27 28 3,116,100 3,247,900 3,385,300 3,528,500 29 30 3,209,100 3,344,900 3,486,400 3,633,800 31 32 3,305,000 3,444,800 3,590,500 3,742,300
- 15. Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2012 Masa Golongan IV Kerja a b c d e 0 2,436,100 2,539,200 2,646,600 2,758,500 2,875,200 1 2 2,508,900 2,615,000 2,725,600 2,840,900 2,961,100 3 4 2,583,800 2,693,100 2,807,000 2,925,700 3,049,500 5 6 2,660,900 2,773,500 2,890,800 3,013,100 3,140,500 7 8 2,740,400 2,856,300 2,977,100 3,103,100 3,234,300 9 10 2,822,200 2,941,600 3,066,000 3,195,700 3,330,900 11 12 2,906,500 3,029,400 3,157,600 3,291,100 3,430,300 13 14 2,993,200 3,119,900 3,251,800 3,389,400 3,532,800 15 16 3,082,600 3,213,000 3,348,900 3,490,600 3,638,200 17 18 3,174,700 3,308,900 3,448,900 3,594,800 3,746,900 19 20 3,269,400 3,407,700 3,551,900 3,702,100 3,858,700 21 22 3,367,100 3,509,500 3,657,900 3,812,700 3,973,900 23 24 3,467,600 3,614,300 3,767,200 3,926,500 4,092,600 25 26 3,571,100 3,722,200 3,879,600 4,043,700 4,214,800 27 28 3,677,800 3,833,300 3,995,500 4,164,500 4,340,600 29 30 3,787,600 3,947,800 4,114,800 4,288,800 4,470,200 31 32 3,900,600 4,065,600 4,237,600 4,416,900 4,603,700
- 16. Pertama-tama, kedelai harus direndam dalam air dingin bersih selama 1,5 jam supaya mengembang dan memudahkan kulit kedelai lepas. "Jangan lupa dicuci lagi sebelum memasuki proses giling yang diikuti perebusan santan kedelai," ujar Saidih. Perebusan santan kedelai itu cukup 10 sampai 15 menit dengan suhu 300 derajat celcius. Sesudah itu, santan kedelai yang sudah matang disaring lalu dicampur dengan air rebusan kedelai yang terfermentasi. "Diamkan saja 10 sampai 15 menit, lalu cetak dan potong-potong, tahunya siap untuk di masak apa saja," kata Saidih. Dia juga berpesan tahu yang sudah jadi namun belum akan dijadikan masakan, masih harus direndam dalam air panas supaya awet. 2 Cara membuat tahu Bahan : 2 KG kedelai, 1ml asam cuka putih atau bisa juga menggunakan batu tahu (Kalsium Sulfat atau CaSO4), dan air secukupnya. Alat pembuatan tahu : Kain pengaduk Cetakan Keranjang Rak bambu Tungku atau kompor Alat penghancur (alu) Ember besar Tampah (nyiru) Kain Saring atau kain blancu Langkah langkah pembuatan tahu : 1. Plih kedelai yang bersih dan besar ukurannya, kemudian cuci sampai bersih. 2. Rendam kedelai dalam air bersih selama 8 jam, Usahakan seluruh kedelai tenggelam. Dalam proses perendaman ini kedelai akan mengembang. 3. Bersihkan kembali kedelai dengan cara dicuci berkali kali. Usahakan kedelai ini sebersih mungkin untuk menghindari kedelai cepat masam. 4. Hancurkan kedelai dengan cara ditumbuk dan secara perlahan tambahkan air sedikit-demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk bubur. 5. Masak bubur kedelai dengan hati-hati pada suhu 70-80 derajat (biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak). Ingat untuk menjaga agar kedelai jangan sampai mengental. 6. Saring bubur kedelai tersebut bersama batu tahu atau asam cukup, sambil diaduk secara perlahan. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu (gumpalan).
- 17. 7. Endapan itu kemudian siap untuk di press dan di cetak sesuai ukuran dan keinginan anda.
- 18. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok di negeri ini, yang termasuk dalam makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung sangat banyak gizi dan cukup mudah untuk diproduksi. Untuk memproduksi tahu bahan-bahan yang dibutuhkan hanya berupa kacang kedelai. Tidak heran jika saat ini kita dapat menemukan banyak sekali pabrik pembuatan tahu, baik dalam bentuk usaha kecil dan usaha menengah yang masih menggunakan cara konvensional ataupun usaha-usaha yang sudah cukup sukses dengan cara pembuatan yang lebih modern. Berdasarkan hal-hal diatas maka kami tertarik untuk menjadikan Pabrik Pembuatan Tahu sebagai bahan makalah proses produksi kami. Lokasi Pabrik pembuatan tahu yang kami pilih terletak di daerah âĶâĶâĶâĶâĶâĶâĶ... Pabrik ini merupakan pabrik pembuatan tahu yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM). Cara pembuatan tahu-pun masih dengan cara konvensional sehingga peran individu atau dalam hal ini para pekerja sangatlah besar didalam proses pembuatannya. Pabrik yang berdiri sejak tahun âĶâĶâĶâĶâĶ. ini didirikan oleh âĶâĶâĶâĶâĶâĶ.. Pabrik pembuatannyapun dibangun dalam kompleks rumahnya sendiri, dan masih bertahan sampai hari ini. Proses pembuatan tahu ini berlangsung di sebuah ruang berukuran 10 m x 7 m. Dan didalam ruang ini proses produksi tahu berlangsung secara konstan. Didalamnya terdapat âĶ.. pekerja dengan pembagian tugas masing-masing. Ada yang bertugas menggiling, menguapi, dan menyaring (âĶ. orang). Ada yang bertugas untuk mencetak (âĶ. orang). Ada yang bertugas untuk mengaturnya dalam kaleng-kaleng besar sebelum akhirnya direbus (âĶ.orang). Dan ada pula yang bertugas untuk menggoreng tahu-tahu yang sudah jadi (âĶ. orang). Di dalam ruangan tersebut peralatan yang digunakan dapat dibilang sederhana dan masih sangat tradisional. Saat pertama memasuki pintu ruangan kita akan melihat sebuah mesin uap konvensional yang terbuat dari 2 buah drum yang berfungsi sebagai penangkap uap. Uap atau panas yang dikumpulkan oleh drumpun berasal dari kayu yang dibakar bukan mesin uap. Jadi awalnya kayu akan dibakar di dekat drum tersebut. Lalu uap panasnya akan terkumpul dalam drum sebelum akhirnya akan disalurkan melalui pipa-pipa besi ke bak-bak penampungan. Teknik ini merupakan pengganti teknik perebusan sari kedelai, jadi pabrik ini tidak merebus sari kedelai mereka melainkan meggunakan teknik penguapan. Selain itu di dalam ruangan juga terdapat 1 mesin penggiling. Jumlah mesin penggiling yang hanya satu-satunya inilah yang menurut kami menjaga kontinuitas dari proses produksi tahu. Selain itu juga terdapat 4 bak dari batu yang digunakan sebagai wadah untuk menguapi sari kedelai dan juga sebagai tempat penampungan air. Lalu ada 4 bak plastik yang digunakan untuk mengendapkan tahu. Ada 25 cetakan dari kayu untuk mencetak tahu. Ada banyak sekali kaleng- kaleng besar yang nantinya akan digunakan sebagai wadah saat tahu dirabus. Dan sebuah
- 19. penggorengan besar yang menggunakan kayu bakar untuk menggoreng tahu. Serta rak-rak dari kayu untuk menampung tahu-tahu yang sudah tercetak. Dengan semua peralatan sederhana diatas pabrik ini berdiri dan menghidupi para karyawannya sejak tahun 1983 hingga saat ini. Tahu yang diproduksi di pabrik Pak H. Lani ini merupakan suatu produk yang dikenal dengan nama Tahu Jambi. Sekilas kita pasti bingung mendengar nama tahu Jambi. Sebenarnya tahu ini adalah Tahu Sumedang biasa. Tapi karena pak Haji ingin sesuatu yang berbeda dari nama tahu produksinya maka tahu inipun diberi nama Tahu Jambi. Sesuai dengan nama kampug halaman pak Haji. Pabrik ini dibangun oleh pak haji sendiri jauh sebelum ia berkeluarga. Dan merupakan suatu usaha yang dirintis sejak ia masih muda. Saat ini pendapatan bersih yang dikumpulkan perhari dapat mencapai lebih dari Rp. âĶâĶâĶâĶâĶ.,-. Jadi dapat dikatakan bahwa pembuatan tahu ini merupakan bisnis yang menjanjikan. Dalam sehari pak âĶâĶâĶâĶâĶâĶmembutuhkan âĶâĶâĶ..kg kacang kedelai untuk memenuhi kuota produksi mereka. Kacang kedelai ini didapat dari para pemasok yang memang sudah menjadi kepercayaan pak Haji karena menurutnya, para pemasok ini memberikan kacang kedelai dengan kualitas yang cukup bagus dengan harga yang pantas-tidak dimahalkan. Selanjutnya tentu kacang kedelai tersebut akan diproses oleh para pekerjanya menjadi tahu. Dari âĶâĶ.. kg kacang kedelai yang ada, nantinya akan diubah menjadi Âą âĶâĶâĶâĶ.cetak tahu. Masing-masing cetakan tahu tersebut biasanya dijual dengan harga Rp. âĶâĶâĶâĶ..,- hingga Rp. âĶâĶâĶâĶ.,-. Secara kasar dapat dihitung pendapatan pak âĶâĶâĶâĶ..adalah Rp. âĶâĶâĶâĶâĶ. ,- dengan omzet inilah bisnis tahu ini dibangun dan terus dipertahankan. Namun tentu saja tidak semua tahu akan laku di pasar. Pasar terbesar dari produk tahu ini menurut pak âĶâĶ.. adalah para penjaja gorengan. Masing-masing dari mereka biasanya memesan hingga 7 papan (cetakan) tahu setiap hari. Begitulah pabrik tahu milik Pak H. Lani terus berdiri hingga saat ini. Dengan modal yang tidak terlalu besar dia bisa memperoleh omzet yang lebih dari cukup untuk menggaji para karyawan, modal usaha, dan menghidupi keluarganya sendiri tentunya. Maka dapat disimpulkan bahwa produksi tahu ini merupakan suatu bisnins yang menjanjikan. Menyerap tenaga kerja. Dan jarang sekali mengalami kerugian karena besarnya pasar yang ada di Indonesia. B. RUMUSAN MASALAH Untuk menjaga keseimbangan konsep yang akan kami bahas selanjutnya maka kami menyertakan rumusan masalah yang terkait dengan isi dari makalah kami ini, yaitu tentang âBagaimanakah proses pembuatan tahu secara konvensional?â
- 20. C. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan makalah ini secara umum adalah untuk memberitahukan kepada para pembaca tentang proses pembuatan tahu secara konvensional dan beberapa informasi penting lainnya seperti omzet yang didapat. Sedangkan tujuan khusus dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Pengantar Bisnis yang diberikan. D. SASARAN PENULISAN Makalah ini dibuat dengan sasaran penulisan awal civitas akademika Universitas Gunadarma. Namun tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang diluar Universitas Gunadarma untuk ikut membacanya. E. MANFAAT PENULISAN Manfaat dari penulisan makalah ini adalah: 1. Agar pembaca dapat mengetahui proses pembuatan tahu secara konvensional. 2. Agar pembaca memiliki konsep yang jelas mengenai bisnis tahu. 3. Agar bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca.
- 21. B A B II PROSES PRODUKSI Proses pembuatan tahu jambi sebenarnya sama saja dengan proses pembuatan tahu lainnya. ïķ Bahan-bahan: Kacang Kedelai Air Batu tahu ïķ Alat Ember besar Tampah (nyiru) Kain Saring atau kain blancu Kain pengaduk Cetakan Keranjang Rak bambu Tungku atau kompor Alat penghancur / mesin penggiling ïķ Langkah-langkah (proses) pembuatan tahu jambi adalah sebagai berikut: Kedelai yang tersedia dicuci hingga bersih. Lalu kedelai yang sudah bersih tersebut direndam dalam air selama Âą 2-3 jam. Setelah itu kedelai yang ada siap digiling. Setelah digiling kedelai yang sudah halus tersebut kita masukkan dalam bak-bak untuk selanjutnya diuapi. Setelah diuapi selama Âą 10 menit kemudian selanjutnya dipindahkan ke kain penyaring dan dibutuhkan waktu Âą 10 menit agar sari kedelai dapat terpisah dari ampasnya. Untuk mempermudah proses terpisahnya sari kedelai dari ampasnya maka ditambahkan air sambil terus diaduk-aduk. Ampas tahu akan tetap bertahan dalam kain sementara sari dari kedelai akan jatuh kedalam bak yang sudah disiapkan dibawahnya. Ampas tahu yang tertahan pada kain lalu dibuang, sedangkan sari tahu dalam bak akan diolah lebih lanjut untuk menjadi tahu. Sari tahu yang ada dalam bak kemudian akan ditambahkan biang/bibit (air tahu) secara terus menerus sambil terus diaduk untuk memisahkan sari kedelai dari air biasa. Penambahan biang/bibit (air tahu) bertujuan agar sari kedelai dalam bak dapat mengendap dengan baik.
- 22. Proses inipun memakan waktu Âą 20 menit sampai air akan terpisah dari sarinya. Setelah itu air biasa tersebut akan disedot hingga terpisah dari sari kedelai. Air ini tidak selanjutnya dibuang, melainkan digunakan untuk menjadi biang/bibit (air tahu) pada proses diatas. Setelah yang tersisa dalam bak hanyalah sari kedelai, maka sari-sari tersebut akan diangkat dengan menggunakan penyaringan untuk seterusnya dimasukkan ke cetakan tahu. Setelah dirasa sudah cukup maka cetakan kemudian ditutup. Proses ini berfungsi untuk memberi bentuk pada produk tahu yang nantinya diasilkan sekaligus unutk meniriskan air yang masih tertempel pada sari kedelai tersebut. Lama penyimpanan dalam cetakan Âą 15 menit. Jika kita ingin tahu yang lebih keras kita tinggal menambah waktu pendiaman dalam cetakan. Kemudian tahu yang sudah tercetak tersebut akan di rebus Âą 1 jam, hal ini dilakukan untuk mengurangi kelembekan tahu. Sekaligus untuk menjadikan tahu lebih tahan lama.
- 23. B A B III PENUTUPAN A. KESIMPULAN 1. Mendukung konsep yang sudah disebutkan diatas bahwa pembuatan tahu tidak membutuhkan modal yang besar. Dan bahan dasarnya pun sangat sederhana serta mudah didapat. 2. Bahwa pembuatan tahu memberikan omzet yang cukup besar. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai titik impas. 3. Untuk proses pembuatan tahu yang konvensional seperti ini dibutuhkan cukup banyak tenaga kerja, sehingga membuka lapangan pekerjaan. B. SARAN 1. Agar kebersihan dari tempat usaha dapat lebih diperhatikan. 2. Agar pemerintah lebih memperhatikan UKM saperti ini karena selain beromzet, juga menyerap cukup banyak karyawan. 3. Agar jumlah pabrik tahu yang beroperasi secara modern dapat sedikit ditekan oleh pemerinta agar pabrik-pabrik konvensional seperti ini dapat terus berkembang dengan baik.
- 24. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tahu merupakan makanan yang digemari masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah hingga atas. Keberadaannya sudah lama diakui sebagai makanan yang sehat, bergizi dan harganya murah. Hampir ditiap kota di Indonesia dijumpai industri tahu dan tempe. umumnya industri tahu dan tempe termasuk ke dalam industri kecil yang dikelola oleh rakyat dan beberapa di antaranya masuk dalam wadah Koperasi Pengusaha Tahu dan Tempe (KOPTI). Proses pembuatan tahu masih sangat tradisional dan banyak memakai tenaga manusia. Bahan baku utama yang digunakan adalah kedelai (Glycine spp). Konsumsi kedelai Indonesia pada Tahun 1995 telah mencapai 2.287.317 Ton (Sri Utami, 1997). Sarwono (1989) menyatakan bahwa lebih dari separuh konsumsi kedelai Indonesia dipergunakan untuk diolah menjadi tempe dan tahu. Shurtleff dan Aoyagi (1979) memperkirakan jumlah pengusaha tahu di Indonesia sekitar 10.000 buah, yang sebagian besar masih berskala rumah tangga, dan terutama terpusat di Pulau Jawa, sebagai bandingan di Jepang sekitar 38 000 buah, di Korea 1 470 buah, Taiwan 2 500 buah dan Cina 158 000 buah. Air banyak digunakan sebagai bahan pencuci dan merebus kedelai untuk proses produksinya. Akibat dari besarnya pemakaian air pada proses pembuatan tahu dan tempe, limbah yang dihasilkan juga cukup besar. Sebagai contoh limbah industri tahu tempe di Semanan, Jakarta Barat kandungan BOD 5 mencapai 1 324 mg/l, COD 6698 mg/l, NH 4 84,4 mg/l, nitrat 1,76 mg/l dan nitrit 0,17 mg/l (Prakarindo Buana, 1996). Jika ditinjau dari Kep-03/MENKLH/11/1991 tentang baku mutu limbah cair, maka industri tahu memerlukan pengolahan limbah. Pada saat ini sebagian besar industri tahu masih merupakan industri kecil skala rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan unit pengolah air limbah, sedangkan industri tahu dan tempe yang dikelola koperasi beberapa diantaranya telah memiliki unit pengolah limbah. Unit pengolah limbah yang ada umumnya menggunakan sistem anaerobik dengan efisiensi pengolahan 60-90%. Dengan sistem pengolah limbah yang ada, maka limbah yang dibuang ke peraian kadar zat organiknya (BOD) masih terlampau tinggi yakni sekitar 400 â 1 400 mg/l. Untuk itu perlu dilakukan proses pengolahan lanjut agar kandungan zat organik di dalan air limbah memenuhi standar air buangan yang boleh dibuang ke saluran umum. 1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan : Tujuan Kegiatan ini adalah mengkaji dan mengembangkan teknologi pengolahan air limbah khususnya pengolahan air limbah industri tahu yang sederhana, murah dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia, sehingga dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Sasaran : Sasaran dari kegiatan ini adalah membuat prototipe unit alat pengolahan air limbah industri tahu yang murah dan sederhana, serta mengkaji karakteristik dan efisiensi pengolahan terhadap beberapa parameter kualitas air limbah serta mengkaji kelayakan alat secara ekonmis. 1.3. Manfaat Teknologi tersebut dapat disebarluaskan dan dapat dimanfaatkan atau ditiru oleh masyarakat.
- 25. II. PROSES PEMBUATAN TAHU DAN TEMPE 2.1. Proses Pembuatan Tahu Tahu merupakan makanan yang terbuat dari bahan baku kedelai, dan prosesnya masih sederhana dan terbatas pada skala rumah tangga. Suryanto (dalam Hartaty, 1994) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tahu adalah makanan padat yang dicetak dari sari kedelai (Glycine spp) dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein, kemudian mengumpulkannya, sehingga terbentuk padatan protein. Cara penggumpalan susu kedelai umumnya dilakukan dengan cara penambahan bahan penggumpal berupa asam. Bahan penggumpal yang biasa digunakan adalah asam cuka (CH3COOH), batu tahu (CaSO4nH 2O) dan larutan bibit tahu (larutan perasan tahu yang telah diendapkan satu malam). Secara umum tahapan proses pembuatan tahu adalah sebagai berikut : Kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan disortasi. Pembersihan dilakukan dengan ditampi atau menggunakan alat pembersih. Perendaman dalam air bersih agar kedelai dapat mengembang dan cukup lunak untuk digiling. Lama perendaman berkisar 4 - 10 jam. Pencucian dengan air bersih. Jumlah air yang digunakan tergantung pada besarnya atau jumlah kedelai yang digunakan. Penggilingan kedelai menjadi bubur kedelai dengan mesin giling. Untuk memperlancar penggilingan perlu ditambahkan air dengan jumlah yang sebanding dengan jumlah kedelai. Pemasakan kedelai dilakukan di atas tungku dan dididihkan selama 5 menit. Selama pemasakan ini dijaga agar tidak berbuih, dengan cara menambahkan air dan diaduk. Penyaringan bubur kedelai dilakukan dengan kain penyaring. Ampas yang diperoleh diperas dan dibilas dengan air hangat. Jumlah ampas basah kurang lebih 70% sampai 90% dari bobot kering kedelai. Setelah itu dilakukan penggumpalan dengan menggunakan air asam, pada suhu 50oC, kemudian didiamkan sampai terbentuk gumpalan besar. Selanjutnya air di atas endapan dibuang dan sebagian digunakan untuk proses penggumpalan kembali. Langkah terakhir adalah pengepresan dan pencetakan yang dilapisi dengan kain penyaring sampai padat. Setelah air tinggal sedikit, maka cetakan dibuka dan diangin-anginkan. Diagram proses pembuatan tahu ditujukkan seperti pada gambar 1, sedangkan diagram neraca masa untuk proses pembuatan tahu ditunhjukkan pada gambar 2.